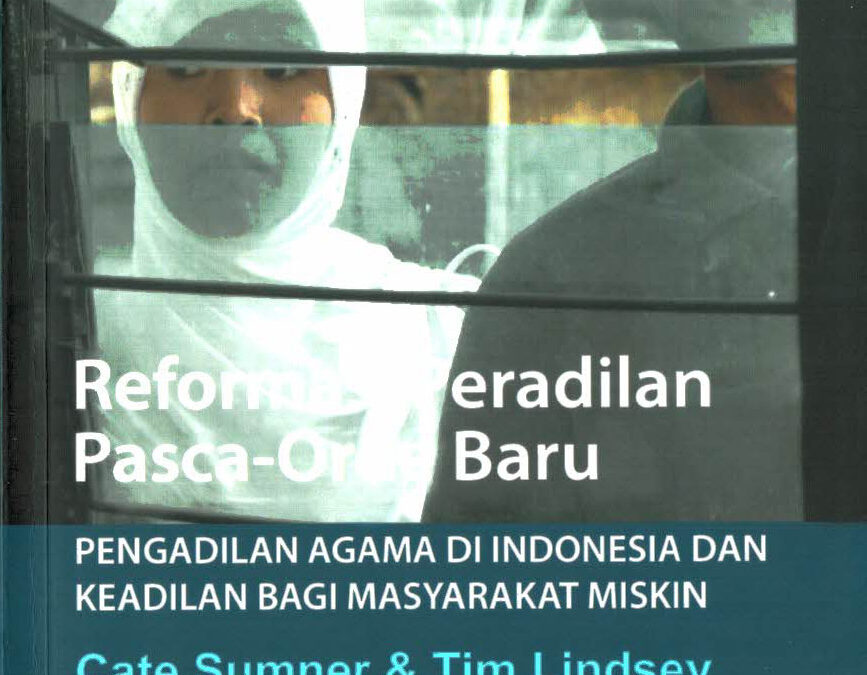ISIF Cirebon – Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim, tetapi sejak awal berdirinya, Indonesia tidak mengambil bentuk negara agama. Para pendiri bangsa memilih jalan tengah: membentuk negara yang menjamin kebebasan beragama, sekaligus tidak tunduk pada tafsir keagamaan tertentu. Pancasila menjadi dasar negara yang menampung keberagaman dan menjadi titik temu antara nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan.
Namun, ini bukan berarti hubungan antara agama dan negara di Indonesia selalu tenang. Sejak awal, terutama dalam konteks Islam, selalu ada perdebatan dan negosiasi. Islam, sebagai agama yang membawa nilai-nilai hukum dan sosial, memiliki pengaruh besar dalam masyarakat. Di sisi lain, negara memiliki kepentingan menjaga kesatuan, stabilitas, dan keadilan bagi semua warganya, tak peduli latar belakang agama mereka.
Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa negara kerap mengambil posisi sebagai penengah. Di masa Orde Baru, negara cenderung menekan ekspresi politik Islam. Zaman pemerintahan Soeharto antara tahun 1966 hingga 1998, suatu periode ketika Islam, seringkali ditafsirkan berpotensi menjadi ancaman politik terhadap negara yang terpusat, otoritarian, dan sekuler yang telah dibentuk oleh militer.
Namun setelah Reformasi 1998, ruang ekspresi semakin terbuka. Banyak pembatasan atas ekspresi identitas Muslim yang diterapkan selama Pemerintah Orde Baru, dicabut tidak lama setelah kejatuhan Soeharto, yakni pada saat demokratisasi Indonesia menuju era keterbukaan baru. Hal ini mengakibatkan munculnya identitas Islam yang begitu marak dalam kehidupan pribadi dan publik, termasuk dalam politik.
Kelompok-kelompok Islam, baik yang besar maupun kecil, mulai menyuarakan kembali aspirasi untuk membentuk masyarakat yang lebih Islami, termasuk lewat penerapan hukum syariah.
Tentu saja, aspirasi ini tidak tunggal. Ada yang menginginkan penerapan syariah secara penuh, ada pula yang memandang syariah sebagai nilai moral yang bisa hidup berdampingan dengan hukum nasional. Perdebatan ini semakin hidup dalam masyarakat dan politik Indonesia. Di tengah dinamika itu, muncul pertanyaan: bagaimana negara dan agama berdialog secara sehat?
Salah satu ruang dialog itu terlihat dalam lembaga Pengadilan Agama. Sebagai bagian dari sistem peradilan negara, namun khusus menangani perkara umat Islam, Pengadilan Agama menjadi tempat menarik untuk melihat bagaimana nilai-nilai keagamaan dan hukum negara saling berinteraksi.
Pengadilan Agama secara konsisten menunjukkan dukungan terhadap nasionalisme negara yang berlandaskan Pancasila. Dalam menjalankan fungsinya, Pengadilan Agama tidak hanya merujuk pada sumber-sumber hukum Islam tradisional seperti Al-Qur’an, Hadis Nabi, dan fikih klasik, tetapi juga mengadaptasi aturan-aturan hukum negara. Adaptasi ini dilakukan meskipun dalam beberapa kasus dianggap bertentangan dengan interpretasi kaum tradisional dari sumber-sumber tersebut.
Pengadilan Agama di Indonesia yang menangani perkara umat Muslim, di satu sisi telah menjadi agen untuk agenda yang lebih membebaskan, yang mencerminkan aspirasi gerakan reformasi yang telah mendominasi kebijakan negara pada era pasca-Soeharto. Akan tetapi, di sisi lain posisi pengadilan agama juga telah banyak mengabaikan aspirasi organisasi Islam konservatif, yang makin tumbuh menonjol pada masa yang bersamaan.
Pendukung Islamisasi yang konservatif seringkali mendapat kritik di Indonesia karena sikapnya yang terang-terangan menunjukkan permusuhan pada perempuan. Misalnya, dalam pengaturan cara berpakaian perempuan, atau dalam membatasi ruang gerak perempuan di masyarakat. Posiai demikian dilihat oleh Pengadilan Agama dengan sebaliknya.
Pengadilan Agama di Indonesia justru dikenal sebagai salah satu sistem hukum keluarga Islam yang paling responsif terhadap hak-hak perempuan di dunia Muslim. Pengadilan Agama telah memimpin upaya-upaya peradilan untuk memperbaiki kedudukan hukum dan kapasitas perempuan untuk menjalankan hak-hak mereka dalam hal hukum keluarga, khususnya hak untuk bercerai dengan cepat dan murah.
Hal ini bisa dilihat pada proses cerai yang cepat dan murah, fleksibilitas dalam perjanjian pernikahan, serta budaya kelembagaan yang simpati terhadap perempuan menjadi cerminan bahwa nilai-nilai Islam dan nilai keadilan sosial bisa berjalan bersama.
Hal ini sebagaimana telah dijelaskan oleh Daniel Lev, yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama selama puluhan tahun memang memiliki budaya lembaga yang bersimpati pada perempuan yang berperkara. Dalam salah satu tulisannya ia menyatakan:
“Aturan hukum keluarga Islam di Indonesia telah lama dianggap sebagai salah satu aturan yang paling liberal di dunia muslim. Perjanjian pernikahan diuraikan dengan jelas dan fleksibel, sebagian karena adanya tekanan dan masukan dari organisasiorganisasi perempuan dalam beberapa puluh tahun terakhir.Selain itu, kantor urusan agama dan pengadilan diam-diam telah bersimpati pada perempuan yang mengalami pernikahan yang buruk.”
Dalam pengamatannya, Daniel menemukan kenyataan bahwa pengadilan agama di banyak kasus justru lebih berpihak kepada perempuan pada kasus-kasus perceraiannya.
“Dalam penelitian saya tentang peradilan Islam, yang pada awalnya sempat didasari oleh beberapa miskonsepsi yang umum terjadi, perlahan-lahan saya menyadari bahwa pengadilan umumnya lebih condong pada perempuan yang merupakan klien utama mereka. Mereka jarang menolak permohonan cerai yang diajukan oleh perempuan,” tambahnya.
Para hakim Pengadilan Agama seperti dinyatakan dalam buku “Reformasi Peradilan Pasca-Orde Baru: Pengadilan Agama di Indonesia dan Keadilan Bagi Masyarakat Miskin,” menyatakan bahwa religiusitas Islam mereka seringkali diungkapkan tanpa banyak merujuk pada fikih dan doktrin. Namun, lebih pada keinginan untuk mencapai apa yang mereka lihat sebagai keadilan gender dan transformasi sosial. Posisi ini, apapun manfaatnya, pada kenyataannya bersilangan dari nilai-nilai agama yang diekspresikan oleh para pendukung Islami konservatif di Indonesia.
Dari uraian yang disampaikan di atas jelaslah bahwa dalam hal Pengadilan Agama, agama dan negara tidak dalam posisi yang bertentangan. Justru, keduanya keduanya berdialog secara terbuka dan jujur sehingga nilai-nilai luhur dari keduanya akhirnya saling menguatkan satu sama lain.
— Disarikan dari buku Reformasi Peradilan Pasca-Orde Baru: Pengadilan Agama di Indonesia dan Keadilan Bagi Masyarakat Miskin (Cate Sumner dan Tim Lindsey. “Reformasi Peradilan Pasca-Orde Baru.” Pengadilan Agama di Indonesia dan Keadilan Bagi Masyarakat Miskin, Lowy Institute: ISIF (2010)).
Link download buku –> Buku_Reformasi_Peradilan